Harus belasan kali setiap harinya dia menarik napas sepanjang mungkin atas rasa geramnya yang tertimbun di ubun-ubun, dan menghembuskan napas itu sekeras mungkin atas rasa kesalnya yang membeban di bahu. Sebab belasan kali setiap hari setongkang jubel batu bara yang disebutnya gunung pembawa sial itu permisi lewat di aliran sungai belakang rumahnya.
Ia tak habis pikir perihal bagaimana bisa gunung pembawa sial itu diizinkan melewati sungai belakang rumahnya, tanpa memikirkan manusia-manusia yang hidup di sepanjang pinggiran sungai itu, yang bisa saja bahkan sudah sering dirugikan.
Terlalu banyak alasan baginya untuk membenci semua hal tentang gunung pembawa sial itu. Mulai dari karena sekian musibah yang gunung itu angkut dan bagi-bagikan di sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, sampai dengan satu fakta yang paling membuat kepalanya gatal akibat kesal, yaitu fakta bahwa orang yang kerap oleh warga desanya sebut ‘bos batu bara’ beserta konco kaki tangannya itu menganggap uang dapat membeli apa saja, termasuk harga dirinya dan harga diri orang-orang di sekelilingnya.
Boleh dibenarkan bahwa sembilan dari sepuluh orang-orang sungai ini adalah orang-orang yang kurang terpelajar, namun ternyata mereka juga manusia, manusia pemilik hak asasi dalam dirinya yang mesti diperhitungkan.
***
“Berapa juta ganti rugi klotok pian yang diserempet tongkang batu bara kemarin, Julak?”
Yang ditanya tidak langsung menjawab, hanya menyeruput secangkir teh panas di hadapannya. Isuh, yang bertanya, memasang raut menanti.
“Tiga juta,” jawabnya santai kemudian seraya mencomot kue untuk dalam piring.
“Hah? Tiga juta? Itu pian yang minta?”
“Tidak, aku tidak minta ganti rugi sepeser pun pada bos batu bara itu. Memangnya kenapa?”
“Ah, tidak, menurut ulun tiga juta itu terlalu sedikit, Julak!”
Julak Hadri hanya senyum ketus mendengarnya. Lantas menghabiskan potongan kue untuk terakhir di tangannya.
“Kenapa pian tidak minta ganti rugi, Julak?” acil Iti, acil warung tempat Julak Hadri minum teh di pagi berkabut ini ikut bertanya.
“Ti, Suh, klotok itu satu-satunya warisan berupa harta yang ditinggalkan almarhum ayahku. Bagiku klotok itu terlalu mahal untuk dapat dinilai dengan uang. Sejujurnya uang tiga juta yang diberikan bos batu bara itu masih utuh ada padaku. Aku bingung akan kuapakan uang itu. Aku tak yakin itu uang halal. Yang kuinginkan saat ini adalah bahwa nanti saat aku pulang aku sudah kehilangan uang itu,” Julak Hadri menghela napas usai menjelaskan semua itu pada Acil Iti dan Isuh. Lega sekali tampak pada raut wajahnya. Sementara Acil Iti dan Isuh terpaku, ada aura haru yang mereka tangkap dari curahan Julak Hadri barusan.
“Terus bagaimana dengan klotok pian itu, Julak?” kejar Isuh. “Bukannya itu satu-satunya mata pencaharian pian?”
“Hus!” Acil Iti menegur keceplosan Isuh itu. Isuh refleks tertunduk seperti menyesal.
Sedang Julak Hadri sedikit mengangkat kepalanya, dengan mata yang bisa disebut menerawang. Tak jelas apa yang ada dalam pikirannya. Entah apakah bisa dikatakan gelisah, cemas, kalut, atau semacamnya.
“Entahlah, Suh, sepertinya rasa benciku pada gunung pembawa sial itu sudah terlalu besar, sehingga aku bisa-bisanya lebih memilih menganggur daripada menggunakan uang ganti rugi dari mereka itu untuk klotokku yang rusak,” ia kembali menghela napas panjang. “ Lagipula Tuhan tidak pernah tidur, Suh.”
Isuh mengangguk beberapa kali pertanda paham. Ia sudah setengah mengerti jalan pikir Julak Hadri yang kini mulai diseganinya.
Kejadiannya pada sore Jumat itu, saat Julak Hadri menghadiri pengajian mingguan di masjid desanya. Lantas salah satu dari sekian belas tongkang batu bara yang lewat setiap harinya pun melintas ketika itu. Dan insiden itu pun terjadi. Insiden yang sejatinya tidak lagi mengherankan apalagi asing baik bagi warga desa tempat tinggal Julak Hadri, maupun desa-desa lainnya yang dilalui gunung pembawa sial kata julak itu.
Sudah telalu sering tongkang besar yang mengusik ketenangan ikan dalam keruh air sungai itu merugikan orang. Bahkan barangkali dapat dikatakan di sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, tongkang itu terus saja meresahkan banyak pihak. Sungai ini telah layaknya napas kehidupan bagi orang-orang yang hidup di sepanjang pinggirannya. Di sungai mereka mencari ikan. Melalui aliran sungai mereka menuju ladang huma menggunakan jukung. Air sungai, yang mereka gunakan untuk mencuci. Air sungai, yang mereka minum. Di atas sungai, mereka membangun jamban-jamban untuk keperluan buang air. Di sungai juga ada transportasi dengan beragam alat transportasi, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang mengangkut manusia hingga yang mengangkut barang. Dan Julak Hadri adalah salah satu pemilik jasa transportasi di sungai ini. Dengan klotok miliknya, dia mengangkut orang-orang ke tempat yang dituju.
Maka betapa tidak kehadiran tongkang besar yang mengangkut batu bara itu akan mengusik dan mengancam kehidupan di sungai ini? Bagaimana jika suatu ketika sebuah klotok mogok di tengah ulak, sedang tongkang batu bara itu akan melintas? Di suatu ketika yang lain seorang bapak-bapak sedang mencari ikan dengan sebuah alat perangkap ikan yang dipasang merentang dari seberang ke seberang sungai, lantas tongkang yang lewat menabrak dan menghancurkannya. Lain ketika lagi, seorang anak sedang menunaikan hajat di dalam jamban reot di atas lanting di tepi sungai, dan tongkang batu bara yang lewat tiba-tiba hilang kendali akibat kelengahan nahkoda yang mengemudikan kapal penarik tongkang itu, lantas tongkang seliwer-seliwer dan akhirnya menyerempet lanting tadi bersama jamban di atasnya, yang masih ada seseorang di dalamnya.
Dan yang seumpama inilah yang dialami Julak Hadri. Klotoknya yang diparkir di tepi sungai belakang rumahnya, hancur diserempet tongkang batu bara. Bagian terparahnya adalah bahwa klotok itu merupakan satu-satunya mata pencaharian yang dimiliki Julak Hadri. Di mana ia harus menafkahi istri dan mengirimkan uang setiap bulan untuk anak laki-lakinya yang kini kuliah di sebuah universitas di ibu kota, dengan rupiah yang dihasilkannya sebanting-banting tulang bersama klotok bersejarah miliknya.
Selanjutnya? Setelah klotok itu tiada? Entahlah, Julak Hadri masih memikirkan perihal dari mana lagi ia harus mengejar rejeki yang diturunkan Tuhan untuknya. Apakah ia harus meminjam uang dari seseorang dan membeli sebidang tanah dengan uang itu untuk ditanaminya padi. Atau mungkin dia gunakan uang pinjaman itu untuk membeli jukung kecil serta seperangkat alat berburu ikan. Atau juga bisa dia merantau ke kampung orang untuk mencari pekerjaan. Atau…
***
Kebenciannya pada apa pun tentang batu bara kian membengkak. Satu sore ia memancing di atas lanting belakang rumahnya. Dan rupanya Julak Hadri harus kehilangan mudnya untuk memancing ketika mendengar gemuruh suara mesin kapal besar penarik tongkang batu bara yang juga besar. Maka seperti biasa, dia harus menarik napas sepanjang yang ia mampu untuk meredam rasa gusarnya. Namun belum sempat tarikan napas itu ia hembuskan, dari arah berlawanan dilihatnya sebuah klotok datang menghamiri kapal penarik tongkang itu. Dan penyebab tertahannnya napas Julak Hadri adalah bahwa klotok tadi membawa dua orang perempuan belia berpakaian minim. Kemudian tampak seorang lelaki berkacamata hitam keluar dari dalam ruang kemudi kapal. Dua perempuan belia tadi dinaikkan oleh pengemudi klotok ke kapal penarik tongkang itu. Mereka disambut oleh si lelaki berkacamata hitam. Setelah itu tampak pula oleh Julak Hadri lelaki berkacamata hitam itu menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik klotok yang tadi membawakan dua gadis belia untuknya. Lantas pemilik klotok turun ke klotoknya kemudian pergi, sedangkan si kacamata hitam masuk ke dalam sebuah ruangan dalam kapal, bergandengkan dua belia yang baru saja dibelinya.
Duhai, betapa ini sangat mengiris hati Julak Hadri. Ia mempersalahkan kehadiran batu bara itu sedemikian rupa. Dianggpanya kehadiran batu bara telah memudahkan orang-orang yang goyah imannya oleh kemiskinan, untuk lebih memilih perbuatan nista agar dapat makan.
Ya, kemiskinan dan tipisnya iman serta sulitnya mendapat pekerjaan yang halaalan thoyyiban, telah mambuat seseorang mengambil pekerjaan menjual kehormatan yang dianugerahkan Tuhan sebagai keputusan. Dan yang terpenting adalah bahwa gunung pembawa sial itulah yang sudah memudahkan keputusan itu dapat dilaksanakan.
Akh! Julak Hadri baru berhasil menghembuskan tarikan napas panjangnya. Dadanya sesak, hatinya miris.
Tiba-tiba Julak Hadri teringat pada anak laki-lakinya, yang tanpa ada pesan dan kabar telah menghilang sejak lima tahun lalu. Sedih hati Julak Hadri mengenang anak laki-lakinya yang pertama itu. Tetlebih jika teringat bagaimana kejadian sehari sebelum anaknya yang bernama Syahrin itu menghilang dari rumah.
“Abah, ulun minta izin pergi ke kota,ulun berniat mencari pekerjaan, Bah.”
“Pekerjaan apa yang kamu cari di luar sana?”
“Ulun berniat melamar kerja di perusahaan batu bara, Bah.”
Julak Hadri tertawa mendengarnya. Entah untuk apa sikap itu dilakukannya. Entah pula ia menertawakan siapa.
“Kenapa, Bah?”
“Hei, perusahaan mana yang bersedia mempekerjakanmu dengan ijazah Tsanawiyah yang kau bawa itu?”
“Bah, katanya di sana peluang untuk mendapat pekerjaan tinggi. Ada banyak yang bisa dikerjakan di sana. Kalau tidak bekerja di kantornya, yahh, paling tidak ijazah Tsanawiyah-ku itu akan membawaku ke pekerjaan lain di perusahaan itu, seperti menjadi kuli angkut, atau sopir truk, atau semacamnya,” Syahrin berusaha meyakinkan abahnya agar bersedia mengizinkan. “Oya, ini yang paling penting, di sana gajinya juga tinggi, Bah!”
“Tidak, abah tidak mengizinkanmu bekerja di perusahaan itu.”
“Bah… Apa abah tidak ingin melihatku seperti amang Mahyun yang setiap kali pulang kampung memakai sepeda motor yang berbeda di setiap kepulangannya? Bahkan dia dikabarkan mempunyai lebih dari satu istri. Bukankah itu pertanda bahwa dia punya banyak uang di balik dompetnya yang tebal itu? Dan satu lagi Abah, Amang Mahyun hanya mempunyai ijazah SD, dan dia bisa menjadi seperti sekarang! Bagimana denganku yang memiliki ijazah Tsanawiah?!”
“Tidak, sekali tidak tetap tidak, abah tetap tidak mengizinkanmu bekerja di perusahaan batu bara…”
“Memangnya kenapa Abah?!” Syahrin memotong pembicaraan abahnya, kali ini dia meninggikan suaranya, tampak raut kekesalan dan kekecewaan berbaur di wajahnya. Lantas dia pergi ke luar rumah meninggalkan abahnya.
Julak Hadri amat menyesalkan sikap anaknya itu, mengingat Syahrin bukan lagi anak-anak yang masih dapat dimaklumi kekeras-kepalaannya. Padahal ia ingin menjelaskan alasannya melarang Syahrin untuk bekerja di perusahaan batu bara. Selain karena kebenciannya pada gunung pembawa sial yang bukan tanpa alasan, ia juga tak habis pikir perihal bagaimana bisa Syahrin ingin mencontoh Mahyun, seseorang di desanya yang berasal dari keluarga dengan perekomian serupa keluarga Julak Hadri, yang kini bekerja di perusahaan batu bara. Namun Mahyun kini beranjak menjadi orang yang sombong, bukan hanya di mata Julak Hadri, tapi nampaknya juga di mata semua orang di desa ini. Bagaimana bisa Syahrin begitu mendewakan uang dan ijazah dalam hidup ini? Berapa kali dia mengaitkan pekerjaan dengan uang uang uang, ijazah ijazah ijazah. Bukankah uang bukan segalanya? Ijazah juga bukan satu-satunya yang dapat menjamin seseorang mendapat pekerjaan.
Dan keesokan harinya, Julak Hadri telah kehilangan Syahrin. Syahrin menghilang dari rumah, tidak ditemukan di mana-mana. Awalnya Julak Hadri tak terlalu menanggapi ini. Karena dia yakin, tidak mungkin Syahrin akan bertahan di luar rumah, ini hanya bentuk kekesalan Syahrin yang sementara. Namun keyakinan itu perlahan lekang setelah tiga hari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, setahun berlalu, hingga saat ini, sudah lima tahun beralalu, Julak Hadri sudah merubah keyakinannya, ‘Syahrin telah benar-benar melupakan keluarganya,’ pikirnya.
Maka sejak saat itu, tinggal satu orang lagi yang bisa ditaruhinya harapan besar untuk dapat menjadi kebanggannya kelak, yang akan mengurusnya di masa tua nanti, yang akan mewarisi dan meneruskan kebenciannya pada gunung pembawa sial itu!
Tiba-tiba ia merasakan ujung kail pancingnya dipatuk ikan di bawah sana…
***
Setahun berlalu setelah klotoknya hancur diserempet tongkang besar pengangkut gunung pembawa sial sore itu. Julak Hadri kini merubah profesi menjadi seorang petani padi di sebuah ladang sewaan dari seorang pemilik banyak tanah di desanya.
“Bang, kapan ya anak kita Upik lulus kuliah?” istri Julak Hadri, Acil Inur, suatu siang yang terik di ladang huma sambil bekerja, bertanya pada Julak Hadri.
“Mana lah aku tahu. Coba nanti kita tanyakan padanya lewat hape Ipin tetangga kita, memangnya kenapa kau menanyakan itu?”
“Entahlah, rasanya aku sudah kewalahan, sudah terlalu lama bekerja keras seperti ini untuk membiayai ongkos kuliah anak kita. Ingin rasanya aku menikmati masa tuaku dengan menghabiskan waktu dalam rumah saja, mendekatkan diri pada Tuhan. Aku juga sudah tak sabar ingin menikmati hasil kerja anak kita jika nanti dia mendapat pekerjaan.”
“Jika kau tidak sanggup lagi bekerja terlalu keras, biar aku saja, aku sanggup bekerja sendiri.”
Acil Inur tidak menjawab, diam saja dan melanjutkan pekerjaannya
***
Pagi itu Acil Inur tidak dapat bekerja karena sakit. Ia sudah memeriksakan penyakitnya pada bidan desa, namun menurut bidan desa, tidak ada penyakit dalam tubuh istri Julak Hadri ini. Mungkin ini adalah penyakit bawaan umur, umur yang semakin tua; semua organ menjadi lemah; tidak lagi dapat berfungsi dengan baik.
Namun rupanya sakit itu membawa berita gembira. Sebab di pagi ini pula, amang Ipin, tetangga Acil Inur, menerima telepon dari Upik bahwa dia hari ini akan pulang. Duhai betapa senang hati Acil Inur mendengarnya. ’Inilah puncak dari rasa lelahku selama ini,’ batinnya.
Maka, Julak Hadri pun tidak jadi berangkat ke sawah setelah mendengar berita baik pagi itu. Suami istri ini berdiam di rumah bersama rasa rindu mereka pada Upik, anak mereka satu-satunya setelah kehilangan Syahrin, anak pertama mereka.
Lebih empat tahun Upik meninggalkan udik kampung halamannya. Hari ini adalah hari kepulangannya. Dan rupanya dia telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Abah dan Ibunya.
Pagi menjelang siang itu…
Sebuah kapal yang biasa menarik tongkang batu bara—namun kali ini tongkang itu tidak ada—berjalan perlahan menepi sungai, semakin perlahan jalannya. Hingga berhenti di tebing sungai belakang rumah Julak Hadri. Semua orang yang melihat heran, penasaran dan mulai berkumpul. Terlebih Julak Hadri dan Acil Inur yang kini terpana.
Tak lama seorang lelaki keluar dari dalam sebuah ruangan kapal yang ternyata besarnya seukuran rumah Julak Hadri itu. Seseorang itu memakai kacamata hitam. Wajahnya tidak asing di mata Julak Hadri dan Acil Inur.
“Upik! Itu Upik!! Anak Julak Hadri!” terdengar teriakan dari kerumunan orang yang menyaksikan kedatangan kapal itu.
“Iya, itu Upik!” suara lain lagi.
“Wah, rupanya kini dia sudah sukses.”
“Iya, sekarang dia menjadi bos batu bara!”[]
________________________________________________
Farid Ma'ruf
Lahir di Desa Batakan, Pelaihari, pada dini hari Kamis, 28 Juli 1994 silam. Sekarang menetap di pojok Kabupaten Barito Kuala, Desa Banua Anyar namanya. Tertarik pada dunia kepenulisan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, dan mulai menulis beberapa bulan setelah ketertarikannya itu. Namun belakangan nyaris tidak pernah menulis lagi, tragis. Blognya, http://faridbraggart.wordpress.com, akun Twitter-nya, @Faridbraggart.







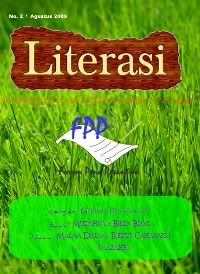
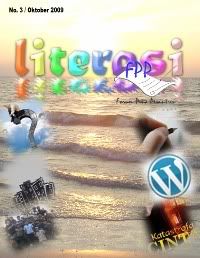

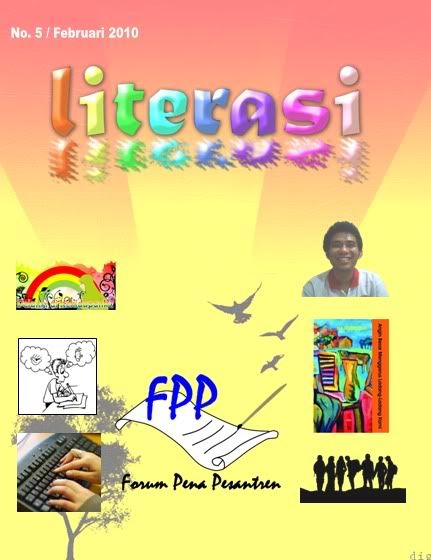

0 komentar: