Samarinda, 18:30 Wita
Berkali-kali aku mengerjapkan mata, yang dapat kutangkap dari penglihatanku saat ini hanyalah bayangan lalu lalang kendaraan bermotor yang tak pernah peduli. Pandanganku masih kabur. Bukan karena mataku minus, ini memang sudah menjadi rutinitasku setiap harinya untuk menjalankan tugas beratku di mana para ayah yang baik harus pulang ke rumah, kembali menemui anak isteri mereka setelah seharian penuh berjibaku dengan pekerjaan yang kian menumpuk. Sedangkan aku? Jangan harap. Di saat manusia mulai mengakhiri aktivitasnya, di saat seperti itulah aku harus bekerja.
Sekarang, kumohon kau diam. Jangan membicarakan apapun tentang diriku. Dan jangan menunututku dengan macam-macam dulu. Menanyakan hal yang menurutku tidak penting bahkan tidak masuk akal. Dan barang tentu aku akan terbahak menertawakan dengan kegilaanmu itu, dengan menanyakan di mana aku lahir, bagaimana keadaan keluargaku sekarang ,parahnya lagi jika kau juga menanyakan anakku ada berapa. Maka kau sudah dapat divonis bahwa kewarasanmu sudah tidak lagi berjalan pada tempatnya. Dan tidak pula kau masih dalam batasan yang sewajarnya. Kau sudah gila Kawan!
Oo…ah, sebenarnya kantukku belum juga reda. Keindahan landscape siang tadi masih tetap mengitari kesadaranku. Tapi, harus bagaimana lagi? Semua orang menuntut keberadaanku di malam-malam mereka. Aku menjadi pahlawan, walaupun hanya untuk sementara waktu. Di waktu malam saja. Dan pada awalnya waktu malam memang begitu sangat menyenangkan.
Waktu malam. Ya, waktu itulah yang selalu kunantikan, waktu yang senantiasa kuelukan kehadirannya. Entah bagaimana jadinya andai sehari saja waktu malam enggan menyentuh kulit bumi. Mungkin kerjaku cuma tidur seharian, bermalas-malasan. Sedangkan waktu siang adalah waktu di mana aku memanjakan kantuk yang menyerangku hebat setelah begadang semalaman suntuk. Singkatnya, waktu siang adalah waktu pembalasan dendamku untuk terlelap.
Asal kau tahu, kini keadaanku sungguh sangat memprihatinkan. Topi yang biasa kukenakan untuk menaungiku dari terik kejamnya matahari terlihat mulai berkarat. Ditambah lagi dengan kondisi yang membopongku, kini tidak kalah memrihatinkan lagi. Beberapa hari ini ia mulai sering sakit-sakitan diterpa angin yang menghantamnya keras tanpa belas kasihan.
Huh, beginilah pemerintah kota memperlakukanku, pekerjaan berat yang kutekuni tak sebanding dengan jerih upah yang mereka berikan. Memuakkan! Aku tidak betah berlama-lama lagi. Aku bosan tinggal di sini!
***
“Sejak kapan kau di sini?” seekor laron tua bertanya dengan nada keingintahuan. Entah dari mana datangnya, ia hinggap tepat di atas kepalaku. Dicermati teliti dari raut wajahnya, sepertinya tidak salah kalau ia memang seekor laron tua. Tak dapat dipungkiri lagi, garis-garis keriput di wajahnya mulai menyelinap di kening serta pipinya yang nampak menciut kempis.
“Entahlah, aku sendiri pun tidak tahu tentang asal-usulku,” jawabku sekenanya, berharap ia mau menjauh dari kepalaku yang mulai terasa gatal.
Seingatku, aku mulai melewati hari-hariku di atas tiang besi ini sekitar 12 tahun yang lalu. Usia yang memang cukup muda untuk anak manusia. Akan tetapi tidak untukku, bagiku 12 tahun umur manusia setara dengan 40 tahun usiaku sekarang.
“Lebih baik aku tidak pernah ada daripada harus seperti ini,” keluhku sedikit meminta simpati.
“Aku mengerti, sudahlah, bersabar saja dengan apa yang ditakdirkannya,” ucap laron tua itu prihatin. Ia merekahkan senyumnya. Ada ketulusan di sana.
“Sekarang begini, andai kau dapat memilih takdirmu, apa yang kau inginkan?” lanjut si laron tua sembari mengepakkan sayapnya, lalu menghadapkan wajahnya persis di hadapanku. Aku kikuk. Tidak biasanya aku ditanyai hal-hal seperti ini oleh siapapun. Membuatku tergagap untuk sekadar membuka mulut, menjawab sesuai dengan apa yang ia kehendaki.
“Aku ingin hidup bahagia layaknya semua orang di dunia ini,” suaraku setengah terisak. Rasanya tak dapat lagi kubendung perihnya kehidupan yang selalu menyiksaku perlahan. Rona keputusasaan tersirat jelas di balik raut wajahku. Tanpa ada harapan sedikit pun.
“Kalau itu memang keinginanmu, baiklah.” Ia pergi tanpa mengucapkan kata perpisahan. Sekilas kuperhatikan, ada yang membuatku takjub dari kekuatan yang ia miliki. Di usianya yang serenta itu, ia masih sanggup terbang tinggi ke atas melawan tekanan udara yang dapat meremukkan tulangnya. Entah ke mana tujuannya. Tanpa mempedulikanku, ia tetap saja menerobos udara malam dengan helaan nafas yang tidak dapat disembunyikannya. Sampai akhirnya samar kudengar pantulan gema langit mengirimkan teriakan laron tua itu kepadaku.
“Akan kusampaikan keinginanmu pada Tuhan!” sesumbarnya.
Apa? Pada Tuhan? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Kupandangi diriku lekat-lekat, tak ada satu pun yang dapat dikatakan kelebihan. Parahnya, banyak sampah-sampah yang membekap betisku hingga mata kaki. Siapa penyebabnya? Huh. Dasar manusia tidak bertanggung jawab, bertingkah seenaknya saja tanpa memikirkan keadaan orang lain. Lagi pula, apa mungkin Tuhan mau memberikan sebagian kecil kasih sayangnya untukku? Tentunya, yang aku tahu Tuhan selalu menyayangi siapapun, tidak pandang bulu, bahkan yang tak mau menyembah-Nya. Dan aku yakin angan-anganku tak lagi membusuk termakan waktu, membusuk seperti aku yang telah dilupakan para bapak-bapak pemerintah kota yang tak ingin lagi merelakan segepok uangnya yang berlimpah. Mereka berjanji merenovasi tubuhku yang lapuk ini. Tapi kapan? Kenyataannya, janji hanya tinggal janji, cuma omong kosong belaka!
Kulirik lagi langit yang kosong melompong, tanpa ada bintang yang merekah malam ini. Bulan pun masih malu menampakkan diri untuk kuajak bercengkrama, mengobrol ngalor-ngidul sampai fajar datang. Aku baru teringat, ke manakah perginya laron tua tadi? Katanya ingin bertemu Tuhan. Namun ke mana ia ingin menuju?
Dulu sekali aku pernah mendengar melalui pengeras suara yang terletak tidak jauh dari kupingku. Pengeras suara yang terhubung ke Mesjid seberang jalan. Mesjid Jami’urrasyidin namanya. Setiap rabu malam, pengajian kitab tauhid yang dipimpin oleh Ustadz Quzwaini selalu sesak dipenuhi kaum laki-laki dari berbagai kalangan. Tua muda tidak menjadi perbedaan di majelis beliau, kebetulan malam itu khusus diperuntukkan bagi laki-laki saja, sedangkan Jumat sore diperuntukkan hanya untuk ibu-ibu.
Aku pun seringkali ikut menyimak penuturan yang beliau sampaikan, hingga aku teringat akan satu hal dari apa yang pernah beliau paparkan.
“Allah itu tidak berhajat pada tempat,’’ tuturnya dengan ciri khas bahasa yang penuh kharismatik. Ya, benar! Tuhan tidak memiliki tempat yang harus dituju, lalu ke mana pergi laron tua itu? Ah, masa bodoh…
***
3 bulan kemudian...
Samarinda , beranda Islamic center, 19:45 wita
Semenjak kejadian malam itu, kehidupanku boleh dikatakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku hidup dalam keramaian zikir, aku dikumpulkan sejejer dengan teman-temanku lainnya dalam megahnya sebuah bangunan yang pada mulanya aku tidak tahu di mana, apa namanya, namun ketidaktahuanku terpecahkan setelah tembok yang kusandari memberitahu, bahwa aku sekarang berada di Islamic Center. Sebuah mesjid sekaligus pusat syi’ar agama Islam yang menjadi primadona kota berjulukan kota tepian ini. Samarinda. Dan asal tahu saja, Mesjid ini juga dikategorikan sebagai Mesjid termegah se-Asia Tenggara! Ah, begitu senangnya aku.
“Kau harus bangga kawan, kau menerangi pejalan kaki yang merindukan Tuhannya,” ucap tembok itu separuh berbisik. Selang beberapa saat aku baru saja tersadar dalam kebingungan. Tempat tinggalku yang dulunya di pinggir jalan yang sesak, aroma knalpot motor murahan, kini terasa lebih nyaman, indah. Tanpa ada suara-suara klakson yang saling berseturu dari satu pengemudi dengan pengemudi di depannya. Debu-debu pasir yang tanpa ampun mencabik wajahku. Semuanya lenyap dari penglihatanku tak berbekas. Yang ada hanya deru tasbih yang beriringan terirama dari saf-saf berbaris rapi. Membuatku tenang, membuatku lebih mensyukuri dengan apa yang kumiliki sekarang. Alhamdulillah, terimakasih Tuhan, dan terimakasih….
Oh, ya! Hampir saja aku melupakannya. Aku memang jahat. Bagaimana nasib laron tua itu, benarkah ia telah bertemu Tuhan? Atau jangan-jangan dia telah mati karena udara malam yang bertubi-tubi, mematahkan rusuk-rusuk rentanya? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Sekurangnya aku harus berterimakasih padanya dengan cara apapun!
“Terimaksih laron tua! Kau telah sampaikan keinginanku pada-Nya…,” suaraku retak memecah keheningan yang mengharu biru. Aku menangis. Aku terdiam pada mendung yang menyusuri langit Mahakam malam ini. [ ]
Banjarbaru, 12 Maret 2011
Teruntuk sahabatku A F, ‘’Tanah etam tak lelah menanti kedatangan kita!’’
____________________________________________________________
Imam Budiman
Spesialisasi puisi ini bisa dipanggil Budi. Katanya lahir di kota tepian Samarinda dua hari sebelum Natal, pada tanggal 23 Desember 1994. Orang yang mengaku sebagai pengagum fanatik Sapardhi Djoko Damono ini, sudah beberapa kali mempublikasikan karyanya di Koran-koran lokal. Seperti Banjarmasin post, Media Kalimantan, dan Radar Banjarmasin. Emailnya: rembulan_limabelas@live.com.







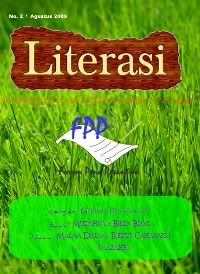
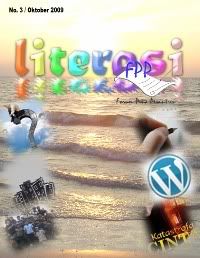

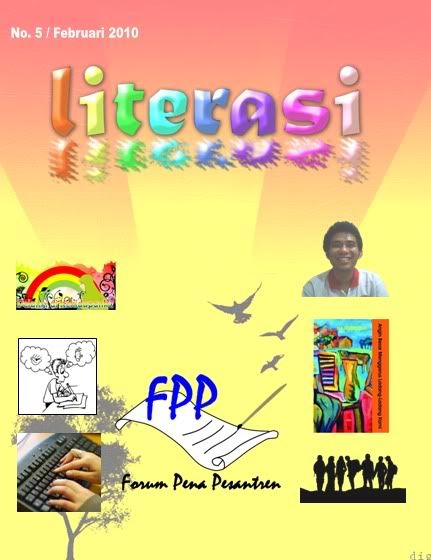

0 komentar: