Aku masih menunggu Arif di samping tembok ujung pesantren. Semak belukar berdiri tinggi melebihi kepalaku. Matahari tampak sangat tua. Sebentar lagi adzan maghrib. Akh, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Arif. Kakiku sudah penat berdiri, dan puluhan nyamuk sudah berusaha memangsaku.
Kresek kresek...
Suara derap langkah datang mendekat. Hatiku lega, penantian ini akan segera berakhir.
Kresek kresek kresek...
Suara itu sepertinya bukan cuma langkah satu orang. Sorotan lampu senter lalu lalang di semak belukar. Aku khawatir, ini bukan langkah Arif. Aku mulai waspada, ambil ancang-ancang, bersiap jika terjadi sesuatu. Aku mulai membayangkan sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam keadaan seperti ini, rasa takut, khawatir dan cemas seakan-akan menjelma menjadi hantu yang mengerikan. Ya, menjelma sesosok hantu yang selama ini diceritakan orang-orang meski aku sendiri tak pernah bertemu dengan fenomena ghaib semacam itu.
Kresek kresek...
Langkah itu terdengar semakin dekat. Sekujur tubuhku lemas. Aku berusaha merunduk menyembunyikan tubuhku di antara ilalang. Kulilitkan sorban di wajahku. Tapi aku masih berharap ini langkah Arif. Mataku terus mengawasi. Lampu senter seperti pistol-pistol yang pernah kutonton di film. Pistol itu mengeluarkan sinar yang akan meneropong titik sasaran menjadi bulatan berwarna merah. Ya. Gerak cahaya senter itu seperti sedang mencari sasaran tembak. Saat aku ingin memastikan, aku terkejut luar biasa.
“Tangkap! Santri...!!!”
Sial. Suara Ustadz Fuad! Kakiku berputar kencang, menembus semak belukar dan menjauh dari tembok. Meninggalkan Ustadz Fuad bersama orang-orang yang bersama beliau, mungkin anggota keamanan OSIS.
***
Pagi ini dingin sekali. kami membalut tubuh dengan sorban. Beberapa santri ada yang sudah tidur kembali, membalas kantuk selama shalat subuh berjamaah di mushalla. Di ujung sana, Zul sedang khusyuk tilawah Al Qur’an. Maklum, ia seorang qori. Ia sering diundang keluar dari tembok suci pondok ini. Apalagi kalau bulan Rajab dan bulan Maulid, pasti kami ikut menikmati rejekinya. Saat Zul datang, satu plastik besar berisi makanan, jadi rebutan kami semua.
Imam dan Dani serius menyapu seluruh lantai asrama. Sedangkan Arif dan aku, konser di ranjang kami yang bersebelahan. Kami bernyanyi bersama, menghayati bait demi bait lagu. Walau dunia luar dan dunia di dalam pesantren ini dibatasi oleh tembok yang sering kami sebut sebagai tembok suci. Namanya modernisasi, lagu-lagu, fashion, dan sebagainya tak bisa dihindari. Apalagi sebulan sekali kami boleh pulang. Saat itulah kami menjadi seperti mereka, seperti anak muda kebanyakan. Banyak di antara kami yang ke warnet, ke Duta Mall, ke pasar Martapura, atau ziarah ke makam ulama.
Di pesantren ini kami juga tidak ketinggalan berita. Setiap hari koran dipajang persis di samping mini market pesantren. Aku selalu ikut berjejal membaca. Yang paling kusuka adalah rubrik sepak bola, dan seleb fashion. Kalau sampai tidak membaca, hatiku merasa ada yang kurang.
“Woiii, diam..!”
Kami berhenti, Johan tampaknya terganggu dengan nyanyian kami. Telinganya ditutup menggunakan bantal. Tapi Zul yang terkaget-kaget mendengar teriakan Johan sepertinya tidak senang. Zul menyaringkan bacaan Al Qur’annya dengan irama-irama merdu hingga kedengaran ke asrama lain. Johan semakin menempelkan bantalnya ke kuping, tapi ia tidak akan berani menyuruh Zul berhenti mentilawah Al Qur’an karena ia berada di pihak yang salah, tidur saat subuh.
Aku dan Arif menyambung kegiatan kami dengan saling bagi cerita. Arif terkenal dengan cerita-ceritanya yang unik, lucu, dan mengagumkan. Apalagi kalau kami baru datang dari libur panjang. Dengan setia kami berjejer di sampingnya, termangu kagum, atau terbahak-bahak.
Di pesantren ini kami tak perlu masak, karena uang iuran perbulan sudah mencakup makan tiga kali sehari. Ada ruang makan khusus untuk kami menyantap menu masakan. Kebiasaan, di ruang makan itu para santri membuat grup makan. Jadi bila pergi makan, seluruh anggota geng itu pasti pergi bersama, makan di satu meja. Bila tak cukup satu meja, dua meja didempetkan jadi satu. Prinsip yang dipegang setiap geng, satu enak semua enak. Tentunya jika satu anggota mendapat kiriman ayam panggang, maka ia harus membagi kepada teman satu gengnya yang lain.
Aku, Arif, Zul, Imam, dan Dani berada dalam satu geng makan. Dani yang rumahnya paling dekat dengan pesantren, tentu paling sering mendapat kiriman berupa makanan.
“Shadaqallahul ‘adziiim…” Zul selesai.
“Makan, yuk..!” teriak Imam dengan suara khasnya yang menggelegar.
“Eh, diam! Makan petir ya kamu??” Johan melampiaskan kekesalannya pada Imam.
“Nggak, suaraku nyaring gini gara-gara makan suara kamu!”
“Sialan! Cari mati?!”
“Ayo, siapa takut!” Jawab Imam sambil memukul lemari.
Suasana subuh yang dingin kian memanas. Untunglah Zul dan Dani berusaha menengahi. Zul memegang badan Imam, dan Dani menangkap badan Johan. Tanpa diduga, Kak Fakhru keluar dari kamarnya sambil memegang kitab.
“Apa lagi ini, heh?” Kak Fakhru langsung menarik leher baju mereka berdua.
“Kalian ini mau belajar atau menjadi jagoan? Johan, sudah berapa kali kamu berkelahi? Sudah tidak terhitung! Kamu Imam, jangan mulai ikut-ikutan! Apa bapakmu menyuruhmu ke sini untuk berkelahi?”
Omelan dan ceramah Kak Fakhrul terus berlanjut, menunda waktu makan kami. Dan di akhir ceramahnya, Imam dan Johan diminta siang nanti menghadap Ustadz Fuad, ketua keamanan pesantren kami. Mereka berdua, Johan dan Imam baru diperbolehkan beraktifitas lagi setelah bersalaman, saling memaafkan.
Kami berlima bergegas menuju ruang makan dengan piring masing-masing. Tapi sebelumnya kami singgah dulu di kantin untuk beli lauk tambahan supaya lebih nikmat, karena pondok cuma menyediakan nasi dan ikan asin untuk sarapan. Kami berjalan beriringan, mengenakan sarung, baju kaos dan peci.
“Seharusnya kamu tadi tak perlu meladeninya, Mam,” Arif sedikit memberi nasehat.
“Betul, aku terbawa suasana, ada rasa gengsi dalam pikiranku.”
“Tampaknya hubungan kita dan Johan makin panas ya?” aku coba angkat bicara.
“Shahih, betul Mal. Mulai dari kita konser tadi, lalu dengan Zul, dan terakhir dengan Imam,” sahut Arif.
Setelah membeli lauk di kantin, kami langsung menuju ke ruang makan. Satu meja kami penuhi berlima, dan kami pun terlena dalam canda tawa.
Usai makan, kami bergegas menuju kran air. Ada beberea para santri wudhu di sana, sementara kami menggunakannya untuk mencuci piring. Sisa-sisa makanan hanyut bersama air bekas wudhu. Kami beranjak pulang dan singgah dulu di koran dinding, tempatnya para santri mendapat berita terbaru yang pastinya selalu sesak oleh santri yang lain.
Aku dan Arif langsung terpana melihat sebuah tulisan: BUAT KAMU YANG BENERAN PENCINTA MUSIK INDONESIA, JANGAN SAMPAI KELEWATAN NONTON KONSER TUNGGAL D’MASIV MALAM MINGGU, 17 OKTOBER 2010 DI LAPANGAN MURDJANI, BANJARBARU!
“Cihuii…!” Arif histeris. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Badan Arif bergetar penuh semangat, semangat jiwa muda yang berkobar.
“Oke, oke, tenang. Kita atur di asrama saja,” saranku.
Kami segera ke asrama, meninggalkan teman-teman lain yang masih asyik membaca koran.
“Jadi jam berapa kita keluarnya?” Persekongkolan dimulai.
“Sore saja.”
“Izinnya?”
“Izin pulang. Bilang saja ada acara keluarga di rumah.”
“Oke, gampang. Lagian masih satu minggu lagi acaranya.”
***
Seluruh santri bersiap menuju ke mushalla untuk melaksanakan shalat dhuha berjamaah seperti biasa.
“Waktu yang kami berikan tinggal 30 menit…!” Suara staf OSIS bagian ibadah membahana di langit pesantren, memperingatkan seluruh santri yang masih santai dan belum bersiap-siap untuk ke mushalla.
Aku mengenakan pakaian seragam pesantrenku; baju koko putih dengan kancing hanya sampai dada dan mengenakan sarung. Jadwal pelajaran hari Ahad ini Tashawuf, Ushul Fiqih, dan Qawaidul Fiqih. Kitab kuambil, kupeluk di depan dada. Sorban tersampir di bahu, dan aku melangkah menuju mushalla bersama Dani yang sudah menungguku.
Sesampainya di mushalla kami duduk bershaf-shaf dengan rapi, mentilawah Al Qur’an sambil menunggu shalat dhuha berjamaah dibawah komando Ustadz Faidhur, kepala bagian ibadah pesantren. Aku duduk di samping Zul.
Tidak berapa lama, Ustadz Faidhur dan Ustadz Fuad datang. Para santri pun berdiri dan meletakkan Al Qur’annya masing-masing. Shalat dhuha dimulai, diimami oleh seorang anggota OSIS. Para anggota OSIS adalah seluruh santri kelas 3 Aliyah, diberi tugas oleh dewan guru untuk membantu mengatur kegiatan santri setiap hari. Jadi mereka berhak memimpin kegiatan ibadah di mushalla atau menghukum kami bila melakukan pelanggaran.
Shalat dhuha dilaksanakan 4 rakaat setiap pagi sebelum masuk kelas. Setelah shalat dhuha biasanya dilanjutkan kultum atau nasehat dari dewan ustadz yang berhadir, atau pengumuman mengenai beberapa masalah.
“Assalamu’alaikum...” Ustad Fuad memegang kendali mushalla. Semua perhatian tertuju pada beliau. Kalau beliau mengumumkan sesuatu, pasti tidak jauh dari masalah keamanan. Panjang lebar beliau menasehati para santri agar tidak melakukan pelanggaran. Dan pengumuman paling pamungkas hari ini adalah seluruh santri dilarang izin pulang atau keluar pondok pada hari Sabtu dan Ahad depan, karena beliau tahu pada malam Ahad itu konser D’Masiv akan diadakan di Lapangan Murdjani yang letaknya masih satu kota dengan pesantren kami.
Arif tertunduk kecewa. Aku cuma memandang sunyi menatap awan sejuk. Pagi yang dingin merona dan penuh embun tiba-tiba pudar di hati kami, para peresap syahdunya musik. Dari belakang aku mengikuti langkah Arif yang mengajakku duduk di kenaungan pohon akasia samping perpustakaan.
“Loncat tembok adalah solusi satu-satunya yang bisa kita lakukan, Mal!” usul Arif.
“Tidak, aku tidak berani. Kualat nanti sama Mu’allim!”
“Masa bodoh sama kualat!”
“Rif! Jaga kata-katamu!”
“Aku frustasi, Mal. Bisa stress kalau begini.”
Air matanya meleleh, penuh kecewa. Bisa kutangkap raut wajah Arif yang setiap hari selalu ceria, kini sembab dan layu. Memang, ia benar-benar pencinta musik sejati.
“Walaupun kita ini pencinta musik, kita tetap harus mengikuti aturan pondok. Bagaimana pun Aku tidak akan meloncat tembok, Rif!”
“Setega itukah kamu padaku? Kita bernyanyi bersama, makan bersama, tidur di asrama yang sama. Ayolah, Mal. Aku pinta kali ini saja. Atas nama persahabatan…” rayu Arif.
Aku tak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Arif terus memaksa sementara aku sendiri tidak memiliki keberanian untuk melanggar larangan Ustad Fuad.
“Kalau kamu tidak mau, aku bisa mengajak Johan. Pasti ia setuju,” ucap Arif menyebut nama Johan.
Aku tersinggung mendengarnya. “Oke, silakan! Yang penting aku tidak ikut!” Langsung kutinggalkan Arif yang mulai terbawa emosi. Aku tak ingin persahabatan ini hancur hanya karena masalah sepele. Kuharap Arif bisa memahami keputusan ini. Langkahku berat, memikul pikiran yang kalut.
***
Aku, Zul dan Imam duduk segitiga di tengah asrama. Sedangkan Dani sedang di ruang tamu menemani abah dan umanya yang datang menjenguk.
“Sepertinya Arif tidak mau lagi berteman dengan kita,” Imam memulai pembicaraan.
“Betul. Tadi saja ia menolak ajakan kita makan bersama dan justru memilih bersama Johan!” timpal Zul.
“Mungkin gara-gara aku menolak ajakannya kabur dengan meloncati tembok,” kataku memberitahu.
“Bisa jadi. Apakah kalian ada solusi agar Arif bisa nonton konser tanpa melanggar aturan?”
“Itu mustahil, Zul. Keputusan Ustad Fuad sudah bulat,” kata Imam.
“Oke, baiklah. Berarti di antara kita berempat harus ada yang menemani Arif nonton konser. Tidak ada solusi lain, demi persahabatan kita selama ini,” Imam menawarkan jalan keluar.
Meski berat, kami tetap bersepakat. Zul mengambil kertas dan pulpen, menulis nama kami dan menggulungnya menjadi 4. Satu gulungan satu nama. Aku meletakkan gulungan itu dalam kopiahku. Kugoncang-goncang, hingga meloncatlah satu gulungan keluar. Imam membuka gulungan itu dengan perlahan.
“Kamal!”
“Sial..!” bathinku.
***
Aku berlari secepat mungkin. Ustad Fuad dan staf OSIS juga masih mengejar. Tujuanku WC! Dalam tasku ada sarung, baju koko, serta peci. Tinggal ganti, lalu berbaur dengan para santri lain di mushalla. Ustad Fuad dan rombongan sudah tertinggal jauh, tapi mereka terus mengejar. Aku masuk ke WC yang tidak jauh dari mushalla. Selamat! Tapi kemana Arif? Ah… mungkin di mushalla.
Saat pintu WC kubuka kembali, rombongan Ustad Fuad sudah tidak terlihat. Mungkin mereka sedang mencari di tempat yang lain. Dengan tergesa aku masuk ke mushalla untuk shalat magrib. Shalatku tidak khuyuk. Usai wirid, Ustadz Fuad masuk ke mushalla. Aku tambah gugup.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”
Hatiku bergetar, jantungku berpacu kencang. Jangan-jangan Ustad Fuad sudah mengetahuinya.
“Saya sedih, ternyata masih ada yang melawan aturan. Ayo, masuk ke sini!”
Anggota keamanan Osis menyeret salah seorang santri.
“Astaga, ternyata Arif!” jantungku berdebar hebat. Aku hanya berani menunduk menghindari tatapan Ustad Fuad. Apa mungkin Ustad Fuad sudah mengetahuinya? Mungkinkah Arif sudah mengatakannya kepada Ustad Fuad? Jika bukan Arif, bagaimana Ustad Fuad mengetahui kalau aku sudah meloncati tembok dan menunggu Arif di luar sana? Aku sungguh merasakan takut luar biasa.
“Jawab pertanyaan saya, Arif. Tadi kami mengejar seorang santri yang telah berani kabur dengan memanjat tembok. Kau pasti tahu siapa orangnya?” Ustad Fuad memandang ke arahku. Kali ini aku benar-benar yakin Ustad Fuad sudah mengetahui bahwa santri itu adalah aku. Lantas untuk apa Ustad Fuad menanyakannya kepada Arif? Apakah Ustad Fuad ingin menunjukkan kepada semua santri bahwa Arif tega mengkhianati temannya sendiri? Jika benar itu yang terjadi, Arif menghadapi masalah besar. Oleh santri, Arif akan disebut sebagai pengkhianat, dan aku akan dijadikan contoh kepada santri lain jika berani melanggar aturan. Rambutku akan di gundul!
“Sebutkan namanya, Arif!” perintah Ustad Fuad.
Glek! Aku benar-benar gugup. Dalam hati aku seperti orang yang berteriak, jangan katakan, Arif. Jangan. Kau akan malu akibatnya nanti. Persahabatan kita sedang dipertaruhkan.
“Kalau kamu tidak mau menyebutkan namanya sekarang jua, panggil mereka,” Ustad Fuad menyuruh staf Osis.
Aku cemas mendengar ucapan Ustad Fuad. Entah apa maksudnya. Para Staf Osis itu kembali bersama empat orang santri lagi. Tentu saja aku mengenalnya. Akh..! Kenapa menjadi seperti ini, bathinku.
“Imam, Zul dan Dani. Bagus..! Sekarang tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Lebih baik kalian ceritakan saja kepada kami apa yang sebenarnya terjadi?” ucap Ustad Fuad menyebut nama mereka satu-persatu.
Melihat mereka bertiga hanya diam, begitu pula Arif yang tertunduk dalam, aku tidak tahan lagi. Kuberanikan diriku untuk membuat pengakuan. Pengakuan ini semoga saja bisa menyelamatkan teman-temanku. “Ana, Ustad yang tadi bersembunyi di balik tembok,” ujarku lirih.
Kuperhatikan semua orang memandang ke arahku. Sebentar lagi staf Osis pasti akan menggelandangku keluar dan menghabisi rambut kesayanganku.
“Jadi kamu, Kamal. Bagus. Kali ini saya akan memberikan hukuman berbeda kepada kamu, juga kalian,” kata Ustad Fuad menunjuk ke arahku, Arif, Iman, Zul dan Dani. “Masih ada satu orang lagi, bawa dia kemari,” Ustad Fuad kembali menyuruh staf Osis.
Keadaan ini sungguh membingungkan. Siapa orang yang dimaksud Ustad Fuad? Apakah dia santri, atau orang lain yang di luar perkiraanku.
“Aku berterimakasih karena kamu telah membocorkan semua rencana mereka, Johan. Tapi bagaimana pun, kamu telah bersepakat untuk menemani Arif kabur dari pondok. Jeleknya kesepakatan itu kamu batalkan sepihak dan akhirnya Kamal dan Arif terjebak. Saya senang pelakunya tertangkap, tapi saya sedih ketika mengetahui ada seorang muslim yang rela menyakiti muslim lainnya. Sengaja saya kumpulkan kalian di musholla agar semua santri mendengar, bahwa sesama muslim itu bersaudara, tidak saja di dalam pondok ini, tapi juga di luar sana. Dari jauh kalian datang kemari untuk mendalami Islam, tapi kenyataannya perbuatan kalian jauh dari Islam. Sampai-sampai di antara kalian ada yang saling jebak, melanggar aturan, dan berusaha melindungi yang salah. Untuk apa kalian berada di sini? Menggundul rambut tidak akan membuat kalian memahami apa yang sudah saya katakan. Kalian hanya takut di gundul, kalian hanya sayang dengan rambut tapi kalian tidak menyayangi Islam sepenuh hati.”
Usai mengatakan itu Ustad Fuad bersama staf Osis langsung meninggalkan kami semua di musholla. Perasaanku tiba-tiba saja berkecamuk memikirkan semua ucapan ustad Fuad. Lantas, bagaimana dengan hukuman kami? Kenapa Ustad Fuad tidak memerintahkan para staf Osis menggundul rambut kami? Apa maksud Ustad Fuad saat mengatakan ia akan memberikan hukuman berbeda kepada kami?
“Ustad, Fuad…” teriakku memanggil dan berlari menghampirinya. Kucium tangan Ustad Fuad dan mengucapkan kata maaf berulangkali. Tangan Ustad Fuad basah oleh tangisanku. Arif, Iman, Zul, Dani dan Johan juga menyusulku dan melakukan hal yang sama. “Kami menyesal, Ustad…” ucap kami bersamaan.
“Semoga kelak kalian menjadi muslim sejati. Saling memaafkanlah kalian sekarang,”ujar Ustad Fuad kepada kami. [ ]
_________________________________________________________







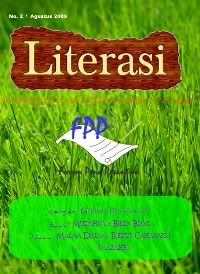
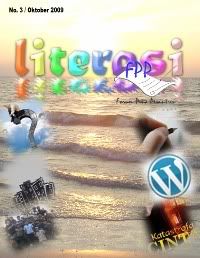

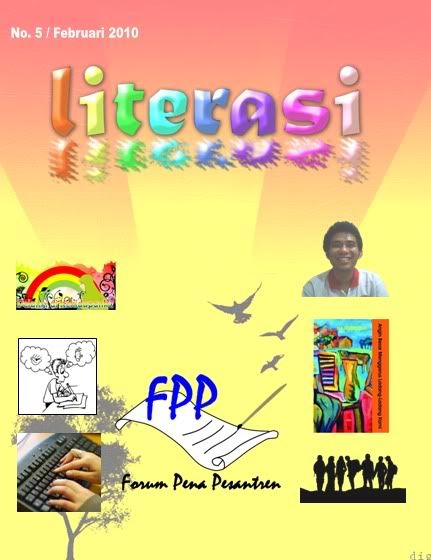

0 komentar: