Aku tinggal di sebuah desa yang tidak terlalu maju, namun juga tidak tertinggal. Tahun ini, aku ingin bisa merayakan tahun baru dengan teman-temanku di kampung.
“Malam ini kita merayakan tahun baru di mana?” tanya Maulana, temanku yang rumahnya bersebelahan dengan rumahku.
“Kenapa kamu tanya begitu?” tanya Malik yang bingung dengan pertanyaan Maulana.
“Bukankah bulan depan Muhammad pindah ke kampung lain,” jelas Maulana kepada teman-teman yang lain.
“Benar kamu bulan ini pindah, Mad?” Abdurrahman mencoba memastikan langsung dariku yang duduk di sampingnya. Rupanya dia juga belum tahu.
“Iya, bapakku pindah tugas ke Ujung Baru,” jelasku pada teman-teman.
“Oke deh, kalo gitu kita ke Banjarbaru saja!” usul Hasan tiba-tiba.
“Betul juga, biasanya kalau tahun baru kota Banjarbaru selalu ramai, apalagi di lapangan Murdjani,” kata Abdurrahman membenarkan.
“Setelah shalat magrib kita berangkat ke sana, bagaimana?” usul Malik.
“Oke, tapi aku mau minta izin dulu sama orangtua,” jawabku.
“Iya, oke, lagipula aku belum pernah ke apangan Murdjani,” kata Hasan membuat kami heran.
“Kamu belum pernah ke lapangan Murdjani, San?” Abdurrahman seolah tak percaya.
“Iya, makanya aku mau ke sana, hehe…”
***
Rencana keberangkatan kami untuk merayakan tahun baru ke lapangan Murdjani berjalan mulus. Orangtuaku mengijinkan pergi ke sana. Lampu warna-warni menghiasi jalanan sekitar lapangan Murdjani. Aku dan teman-teman duduk santai di pinggir jalan sambil menikmati pemandangan dan keramaian malam tahun baru. Tahun depan sepertinya aku tak bisa lagi menikmatinya bersama teman-teman.
“DAARRR…!” Sebuah mercon tiba-tiba meledak di kakiku, entah dari mana datangnya. Aku langsung terlempar ke belakang.
“Aduh… Aduh…”
“Kamu tidak apa-apa, Mad?” tanya teman-teman sambil berusaha membantu aku segera bangun kembali.
“Kakiku terluka…” kataku menahan rasa sakit.
“Malik, cepat ambil mobil!” perintah Maulana. Malik pun tergesa-gesa menuju tempat parkir. Selang beberapa waktu, Malik kembali dengan napas tersenggal. Ia mengkhawatirkan kondisi kakiku dan terpaksa berlari.
“Mobilnya di ujung sana,” ucap Malik menyarankan agar aku segera di bopong menuju mobil yang tak bisa dibawa mendekat. Jalanan yang melingkari lapangan Murdjani sudah mulai macet. Lalu lalang kendaraan saling sambung-menyambung. Malik terpaksa menghentikan mobilnya di tempat yang agak sunyi. Abdurrahman dan Maulana langsung mengangkatku ke dalam mobil. Setelah semuanya naik, mobil pun langsung melesat menuju Rumah Sakit Ulin.
Baru sampai kilometer 32, jalanan sudah macet, penuh dengan kendaraan bermotor. Kami terjebak dan tak bisa bergerak sama sekali. Tepat di samping kiri kulihat Pondok Pesantren Al Falah Putera.
“Sial, macet lagi!” gerutu Malik karena kesal dengan keadaan yang merepotkan ini.
“Ya sudah, kita putar arah saja, ke Rumah Sakit Ratu Zaleha!” usul Maulana.
“Sepertinya bisa,” jawab Malik. Ketika ada kesempatan, Malik pun segera memutar kemudi dan mobil pun berbalik haluan menuju jalur sebelah. Saat sudah tiba di bundaran Banjarbaru, Malik mengumpat kembali. “Aduh, lebih parah lagi rupanya!”
“Sabar ya, Mad,” Abdurrahman mencoba menenangkanku yang tak henti-hentinya mengerang kesakitan. Nyeri di kakiku rasanya tak tertahankan lagi.
Jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Kami belum juga bisa keluar dari kerumunan mobil yang berderet di jalanan. Satu jam kemudian, akhirnya kami tiba di Rumah Sakit Ratu Zaleha, Martapura.
***
Jam dua malam, kedua orang tuaku baru bisa tiba ke rumah sakit. Alasannya pun sama, mereka terjebak macet. Ah, ini adalah malam terburuk yang pernah kulewati. Tadi dokter bilang, lukanya terlanjur parah karena tidak langsung ditangani pihak medis.
Banyak darah yang keluar dan aku membutuhkan donor darah malam ini juga. Selain itu, sempat aku mendengar luka bakar di kakiku terbilang serius. Suasana tegang terjadi. Orang tuaku panik, begitu pula teman-temanku. Perlahan air mataku menetes. Rasa sakit di kakiku perlahan mulai tidak terasa. Pandangan mataku remang-remang. Kepalaku terasa berat. Rasanya lama sekali aku hanyut dalam obat bius yang disuntikkan oleh dokter.
Saat mataku kembali terbuka, kuperhatikan orang-orang di sekelilingku. Semua masih ada di sana. Wajah mereka tak cukup menjelaskan kondisi kakiku. Saat kutanyakan, ada air mata yang menghambur deras saat itu juga, air mata ibu saat meraung-raung menciumi pipiku. Aku dihinggapi rasa bingung yang tak berkesudahan. Semua orang ikut menangis.
Kulihat Bapak meluapkan sesuatu dengan memukul pelan dinding kamar tempat aku di rawat. Aku bingung. Bukankah semuanya baik-baik saja? Kenapa mereka menangis? bathinku. Toh tak ada rasa sakit lagi yang terasa di kakiku. Lihat buktinya. Aku berusaha menggerakan salah satu kakiku yang terkena mercon.
Aneh, kenapa aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak bisa menggerakan kakiku sendiri. Sejurus kemudian, tangisku seperti sedang melengkapi tangisan semua orang. Kemana kakiku? Kemana? Teriakku histeris ketakutan.[ ]
_____________________________________________________________







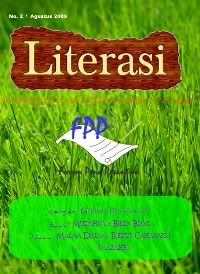
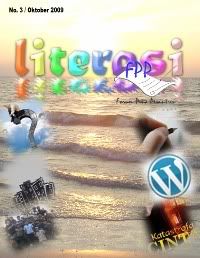

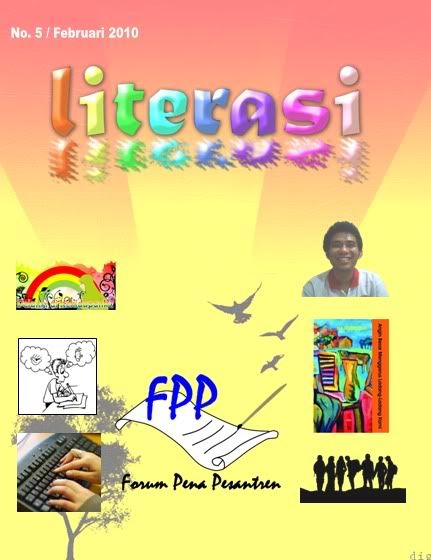

0 komentar: