
(Cerpen ini pernah dimuat di harian Banjarmasin Post pada tanggal 30 Agustus 2009 dengan judul yang sama)
Oleh : Kamal FPP
Hangat mentari pagi mulai terasa. Kabutnya embun masih menghalangi pandangan mata, seolah-olah jelmaan jin yang menampakkan dirinya. Kokok ayam sudah mulai mereda, karena tenggelam oleh suara takbir yang menggema dari masjid-masjid di sekitar pasar Rantau pagi ini.
Hilir mudik pejalan kaki tak terlihat padat seperti hari biasanya. Begitu juga dengan mobil-mobil pembawa sayuran, tukang becak, dan tukang gerobak.
Rasanya hanya aku yang bangun di pagi ini. Teh hangat telah tersedia di hadapanku. Aku duduk di atas loteng rumahku sambil kebingungan melihat semuanya.
Tampaknya ada sesuatu yang mengubah semua ini. Kusiram mataku dengan air teh yang ada di depanku, seakan-akan tak percaya dengan apa yang terjadi.
Jangan-jangan aku cuma mimpi atau menghayal. Tapi ternyata, siramanku tadi hanya buang-buang waktu saja. Ini memang benar. Kejadian ini menyelamkan pikiranku ke dasar lautan imajinasiku untuk menemukan jawabannya.
Ah. Tampaknya pikiranku kehabisan oksigen kalau berlama-lama di lautan ini. Lebih baik aku mencari jawabannya ke langit sana. Mungkin di sana ada yang bisa menjawabnya. Pikiranku melesat dengan cepat menuju langit imajinasi, bagaikan cahaya laser yang bergerak menuju sasarannya.
Di langit pertama, aku bertemu laki-laki berjubah putih berambut panjang sedang berdiri, sambil menatap matahari yang berada di langit keempat. Ah… Mungkin ia tahu jawabannya.
“Pak! Apakah Anda tahu kenapa kota Rantau hari ini sangat sepi?”
“Saya saja masih bingung, mengapa matahari itu bernyala sendiri tanpa menggunakan bensin! Nah, menjawab pertanyaan saya saja saya tak bisa, apalagi menjawab pertanyaan Anda!”
Uh, menyebalkan. Mungkin di langit kedua dan seterusnya, penghuninya sama seperti dia. Lebih baik aku turun ke bumi. Mungkin di tengah hutan pegunungan Meratus sana, ada seorang petapa yang bisa menjawabnya.
Pikiranku turun ke hutan pegunungan Meratus dengan hati-hati supaya tidak tersangkut di dahan pohon ulin nantinya. Hutan pegunungan Meratus yang luas, ditumbuhi beraneka macam pepohonan. Kicauan burung dan deru angin sepoi-sepoi, begitu menyejukkan kalbu. Dedaunan yang tertiup angin, seolah melambai-lambai menyambut kedatanganku.
Aku terus menuju ke dalam hutan ini, menuju rumah tua yang ada di lereng gunung itu.
, suasana terasa semakin mencekam. Ditambah udara dingin yang membuat hutan ini seoalah mati tanpa ada kehidupan. Serigala-serigala hutan sedang bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian dari alam kubur.
Rumah itu semakin dekat saja. Dinding-dindingnya yang terbuat dari kayu ulin, dihiasi lumut-lumut hijau yang tumbuh dengan tenang, tanpa takut dipindahkan oleh sang tuan rumah ke bebatuan. Begitu juga dengan atapnya, beberapa anggrek melekat di atasnya. Tanpa dirasa oleh panca indraku, ternyata aku sudah berdiri di depan pintu rumah tua ini.
Brak…
Tiba-tiba kedua daun pintunya terbuka tanpa dibuka. Kulihat di dalam ada seorang yang telah lapuk dimakan usia. Tangannya yang keriput bergetar dan bergerak ke kanan dan ke kiri, mengitari dupa yang dibakar di hadapannya.
Mulutnya komat-kamit mengucap mantra-mantra yang tak kumengerti apa artinya. Matanya terpejam penuh konsentrasi. Kedua kakinya saling merapat seolah-olah kedinginan.
Aku berdiri mematung semakin kebingungan. Apakah ia bisa menjawab kebingunganku ataukah kejadian di langit pertama tadi terulang kembali? Tapi aku rugi jika aku pulang tanpa jawaban. Perjalanan yang mengerikan ini harus mendapat imbalan yang sesuai.
“Kek, apakah Anda tahu mengapa kota Rantau hari ini sepi?” tanyaku memulai pembicaraan.
“Huahaha.... Huahaha.....”
Tawanya yang meyeringai membuatku tersentak ke belakang.
“Aku laparrr…. Sudah satu minggu aku tak makan daging,” ucapnya sambil mencabut parangnya yang sedari tadi melekat di pinggangnya.
“Jangan…!” teriakku sambil melarikan diri darinya. Aku merasa terbang ke udara. Ah, selamatlah diriku sudah.
Brak…
Aku menabrak ranting-ranting pohon ulin. Dan kini pikiranku terjatuh ke bawah menimpa bebatuan besar yang berlumut. Sepuluh meter dari rumah tua tadi, kakek itu mengejarku sambil mengacungkan parangnya. “Tidak…!”
Kularikan pikiran ini secepat kilat, karena tak mungkin bisa melesat ke udara di hutan yang serimbun ini. Lebih baik aku ke Pondok Pesantren Al Falah saja. Katanya disana itu banyak orang-orang jenius.
Dari luar aku memandang ke dalam. Pesantren ini terlihat sangat indah. Bank santri, balai kesehatan, kantor yayasan, perumahan guru-guru, dan pepohonan tersusun dengan rapi. Gapuranya yang megah, berhiaskan kaligrafi-kaligrafi Arab. Ditambah, air mancur yang tanpa lelah mengeluarkan airnya setiap waktu berada di kirinya. Bunga-bunga kecil yang indah mewarnai kanan dan kiri jalan. Ikan-ikan mas berenang dengan gembira di kolam yang ada di bawah air mancur. Warna putih dan biru melekat kuat di dinding bangunan-bangunannya, sehingga semuanya tampak seperti saudara kembar.
Burung-burung terbang dan kembali ke sarangnya yang bertumpu di dahan-dahan pohon akasia yang berumur paruh baya. Akasia itu tampaknya sangat senang hidup di pesantren ini. Itu tampak dari raut wajahnya. Walaupun wajahnya keriput, tapi senyuman tak pernah luntur dari bibir dan matanya.
Pikiranku terus berjalan ke dalam untuk mencari jawaban yang mebingungkan itu. Aroma bunga yang sedang bermekaran di samping jalan, senantiasa menemani penciumanku sedari tadi. Kumbang dan kupu-kupu berkompetisi untuk mencuri madunya. Tapi itu tidak terjadi pada bunga mawar yang sedang menikmati hangatnya matahari, karena ia menyimpan madunya dibantu oleh duri-duri badannya. Tapi tampaknya ia tak dapat mencegah semut-semut pencari madu yang telah mencium aromanya.
Begitu juga dengan burung-burung gereja. Mereka terbang bermain-main dengan bebas tanpa takut ditabrak oleh pesawat yang hilir mudik untuk menurunkan penumpang dan mengangkutnya kembali di bandara Syamsuddin Noor yang sangat
dekat dengan Pesantren Al Falah. Anak burung itu tampaknya cuma bermain-main saja dari tadi. Sedangkan ibu mereka mencarikan makan dari batang pohon akasia yang dihuni ulat-ulat pohon. Akasia tua itu berterima kasih pada induk-induk burung itu, karena rasa gatalnya akibat ulat-ulat itu berkurang. Sungguh sebuah kehidupan yang menakjubkan mata.
Pesanteren ini tampaknya ditinggal pergi penghuninya. Itu terlihat dari lengang dan kesunyian yang kurasakan saat ini. Kulanjutkan perjalananku mencari jawaban pertanyaanku. Kulihat di asrama-asrama yang dikunci ini dari jendela kacanya. Terlihat beberapa tikus sedang berpesta di kasur yang bergulung tanpa seprai. Di ujung-ujungnya, tampak kelelawar-kelelawar yang tidur dengan nyenyak sambil bergantung, tanpa takut terjatuh atau digigit oleh tikus-tikus nakal.
Tampaknya sudah berminggu-minggu asrama ini ditinggalkan. Sama halnya dengan asrama yang ada di sampingnya. Laba-laba hidup dengan tentram. Rumah-rumahnya bergantung-gantungan di dinding-dinding asrama. Sang betina sedang mengerami telurnya, sedangkan si jantan melekat santai di sarangnya sambil menunggu nyamuk atau serangga yang tersangkut.
Seekor cicak memandangnya dengan geram. Karena nyamuk dan serangga lainnya banyak yang tersangkut di rumah laba-laba itu, sehingga makanannya pun berkurang drastis. Saat seekor kupu-kupu yang tersesat ke dalam asrama, ia terjebak di rumah laba-laba itu. Sang cicak semakin geram, cicak itu melompat menerkam kupu-kupu yang tersangkut itu. Tapi celaka tak dapat ditolak, malahan ia sendiri yang tersangkut di jaring laba-laba yang kuat itu dan kupu-kupu terlepas dari jaring. Sepertinya sang laba-laba itu sudah tahu dengan apa yang akan terjadi. Ia pun tertawa dengan senangnya karena mendapat makanan yang besar. Memang betul asrama-asrama ini lebih dari tiga minggu ditinggal penghuninya.
Pikiranku kembali berjalan menuju perumahan yang ada di depan kelas bertingkat dua itu. Yang di sampingnya tumbuh lebat pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi ke angkasa raya. Rumah-rumah itu tampak sederhana saja. Dengan atapnya yang dibuat dari atap seng yang dipaku, dan dindingnya dari susunan papan yang bercat putih. Sederhana saja. Di pintu rumah-rumah itu terukir nama dalam bahasa Arab. Tampaknya itu nama pemilik rumah. Rumah itu ada lima buah, rumah yang pertama di daun pintunya terukir nama “Murjani”.
Kuketuk pintu itu dengan pelan-pelan sambil mengucapkan salam.
“Assalamu ‘alaikum.”
Suasana hening tanpa jawaban, tanpa sahutan dari dalam rumah. Mungkin rumah ini juga ditinggal penghuninya sama seperti asrama-asrama tadi.
Lima menit kemudian, habislah lima buah rumah itu kuketuk. Sama seperti rumah pertama, empat buah rumah lainnya juga tak menjawab salamku. Aku tak mau kembali dari sini dengan tangan hampa. Pikiranku kembali berjalan mencari jawaban itu.
Kini aku telah berada di belakang rumah tadi. Sebuah telaga yang tampak begitu anggun terletak disana. Tumbuhan-tumbuhan tampak gembira sekali ketika angin menggoyangkan tubuh-tubuh mereka. Sedangkan sekelompok ikan nila terlihat sedang beristirahat di pinggir-pinggir telaga. Pohon jambu muda menaungi mereka sambil berdiri di samping telaga itu.
Tiba-tiba ikan-ikan itu berlari-lari ketakutan. Tumbuhan-tumbuhan berdiam tanpa gerak. Air yang ada di tengah telaga itu bergolak-golak seperti air yang sedang mendidih. Burung-burung yang tadi berkicau, kini berubah menjadi ribut. Angin pun tak meneruskan perjalanannya melewati daun-daun pohon kelapa. Aku merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Suasana yang menenangkan hatiku tadi, serasa seperti mati suri.
“Wuahaha… Wuahaha…” Tiba-tiba muncul di tengah danau itu orang tua dari rimba Meratus tadi yang sedang kelaparan. “Aku laparrr… Aku mau makan daging.” Teriakan itu membuatku lari secepat kilat tanpa mempedulikannya.
Brak…
Pelarianku tampaknya tak berhasil. Kakiku tersandung batu bata tua yang tersusun rapi. Orang rimba itu telah berada di dekatku.
“Hyaa…” Ia mengayunkan parangnya. Tapi lima senti dari leherku, tongkat besi seseorang menahan laju tajamnya parang itu untuk menyentuh kulitku.
Kakek langit! Kakek yang kebingungan di langit tadi menghalangi laju parangnya si orang rimba. Aku menjauh dari mereka. Kududukkan pikiranku yang menggigil karena ketakutan di bawah pohon pepaya yang sedang berbuah. Pepaya ini tampaknya tegang juga melihat mereka berdua berkelahi.
Si orang rimba sangat marah karena mangsanya lolos. Ia keluarkan habis-habisan semua ilmunya. Lima puluh parang keluar dari mulutnya. Parang-parang itu sambung menyambung dan membentuk sebuah formasi naga yang menerjang perut kakek langit. Tapi itu tak mengapa bagi kakek langit yang sudah siap dari tadi. Tongkat besinya jadi banyak dan merapat, sehingga menjadi sebuah pagar yang kokoh. Mulutnya komat-kamit sambil menatap tajam ke matahari di langit.
Tiba-tiba langit berubah menyeramkan. Langit merongrong penuh murka. Kilat menyambar-nyambar mencari mangsa. Dari segala arah, angin berlari dengan cepat menuju si orang rimba. Tapi si orang rimba tetap tegar berdiri di pijakannya. Matanya bernyala-nyala dikuasai amarah. Ia menatap kepadaku. Parangnya langsung melayang ke arahku.
“Mal, cepat ganti baju!” panggil ibu membuyarkan lamunanku.
“Hari ini kita shalat Id di samping pasar,” kata Ayah menimpali.
Ya Ilahi. Hari ini kan hari Idul Fitri. Pantas saja kota Rantau hari ini sepi.[]





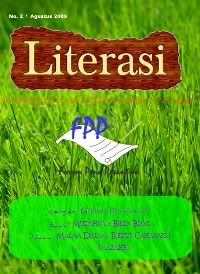
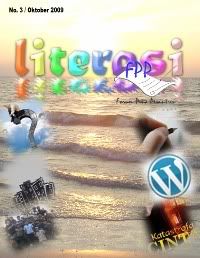

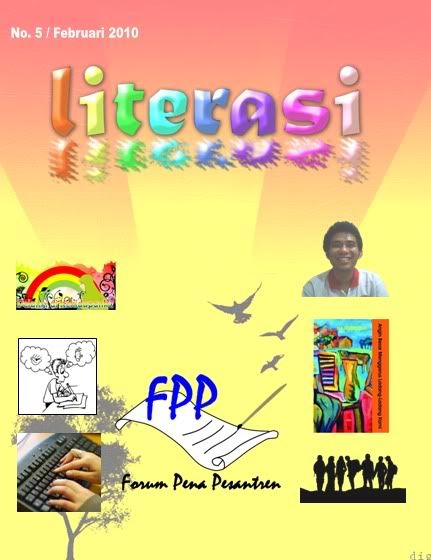

0 komentar: